Pernikahan Anak Bukan Masalah Sepele
Bermula
dari undangan teman saya untuk ikut hadir dalam acara Youth In Action! 2014 di
Universitas Paramadina Jakarta beberapa bulan lalu, seorang teman baik
sekaligus kakak senior ketika kuliah di Sosiologi FISIP UI dulu ternyata
menjadi aktivis dari project UNICEF. UNICEF adalah salah satu lembaga yang
berpartisipasi dalam acara ini, selain berpuluh lembaga/NGO lainnya. Kak
Rukita, nama teman baik sekaligus kakak senior saya tersebut, yang kemudian
menawarkan saya untuk ikut terlibat dalam survei UNICEF terkait acara Girl
Summit 2014. Caranya sangat mudah, saya hanya harus melakukan aksi follow dan mengirim direct message pada akun twitter project UNICEF ini. Dan benar
saja, setiap minggu pertanyaan seputar child
marriage dari akun twitter tersebut masuk ke dalam inbox direct message twitter saya.
Saya,
yang sebelumnya memang belum pernah benar-benar memikirkan masalah child marriage, akhirnya mulai tergerak
untuk ikut memikirkan isu yang satu
ini. Maklum, mungkin karena di lingkungan tempat tinggal saya yang tergolong
areal perkotaan, isu ini tidak marak. Tapi bukan berarti di daerah lain dari
Indonesia, isu ini tidak marak. Sebulanan lalu saya mengobrol dengan seorang
ibu berusia 60an di bis kopaja yang saya tumpangi untuk pergi ke terminal bis
AO di Blok M dari Depok. Ibu ini bercerita kalau dulu, dia dinikahkan ketika
masih berumur 14 tahun—dan itu sering terjadi di daerah Pulau Jawa. Saya tidak
bisa membayangkan jika itu masih terjadi
sampai sekarang. 14 tahun saya baru lulus SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan
kalau diingat-ingat masih merasa belum tahu apa-apa soal pernikahan dan pembentukan
keluarga.
Saya
juga masih mengingat masa sekitar dua tahun yang lalu—waktu itu sekitar bulan
april, dan saya punya seorang teman baik di warung makan yang sering saya
kunjungi setiap hari. Dia adalah seorang perempuan yang bekerja menjaga warung
makan tersebut, tapi umurnya baru 17 tahun. Meski begitu, dari perawakannya,
saya malah merasa dia jauh lebih dewasa daripada saya.
Ia
berasal dari daerah Jawa Barat, di pedesaan yang mungkin tidak usah saya sebut
namanya. Kami berteman baik karena nyaris setiap hari saya makan disitu. Maklum,
waktu itu saya masih kuliah dan warung makan itu sangat dekat dengan rumah
kosan saya. Harganya juga terjangkau, porsinya banyak (itulah kenapa mahasiswa
laki-laki dari kampus saya senang makan disitu), dan makanannya beragam. Enak. Nama
warung makan ini cukup terkenal di kawasan kos-kosan saya itu. Sangat dekat
dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Saya
masih ingat suatu kali dia ingin berpamitan karena akan pulang ke daerah
asalnya. Bukan hanya karena shift menjaga
warung makan itu sudah harus digilir lagi, tapi karena dia akan menikah. Menikah di umur semuda itu, 17 tahun. Ya ampun. Saya
masih sulit membayangkan bagaimana dia harus siap menjadi istri dan ibu di usia
belasan tahun. Bahkan, saya yang waktu itu sudah menginjak umur 21 tahun saja
masih merasa belum siap untuk memikirkan pernikahan—apalagi menjalaninya! Rasanya
masih sibuk dalam tugas sebagai mahasiswa, yang masih mau kuliah, masih harus
memikirkan topik skripsi, masih harus memikirkan UAS yang sebentar lagi, masih
harus memikirkan makalah dan penelitian kelompok, masih harus memikirkan segala
organisasi non-akademis yang saya ikuti di kampus, masih harus memikirkan saya
akan jadi apa setelah lulus, masih harus memikirkan banyak hal. Dan ketika saya
melihat gambar dari UNICEF ini, saya merasa kata-kata dalam gambar ini sangat
benar. Semua yang saya pikirkan tadi—yang membuat saya merasa belum ingin
menikah dulu—terkait masalah pendidikan dan kampus. Itulah kenapa pendidikan
adalah hal krusial yang menentukan child
marriage dari seorang anak.
Saya
tidak tahu apakah teman baik saya itu dipaksa menikah atau menikah karena
kemauannya sendiri. Yang jelas, sepertinya ia memilih calonnya sendiri. Hanya saja,
dia sempat bercerita kalau ia pun kaget ketika tiba-tiba dilamar oleh laki-laki
(yang tadinya dia kenal menyukai kakaknya yang ternyata sudah punya pasangan).
Lalu semua berjalan begitu saja. Sampai akhirnya, beberapa bulan kemudian, dia
memberi kabar pada saya via sms kalau dia sudah menikah dan memiliki bayi
pertamanya. Di umur 17 tahun.
Kembali
mengenai isu child marriage, sebenarnya
pernikahan seperti apa yang dinamakan child
marriage? Berikut yang saya kutip
dari website UNICEF : “Child marriage,
defined as a formal marriage or informal union before age 18, is a reality for
both boys and girls, although girls are disproportionately the most affected.” Jadi,
jika seorang anak perempuan menikah secara formal sebelum usia 18, itu
tergolong child marriage. Dan berarti,
teman baik saya itu, yang sudah menikah dan memiliki anak di usia 17 tahunnya,
mengalami child marriage juga. Dari sejarah,
yang saya lacak, ternyata child marriage ini
merupakan sebuah tradisi bawaan dari berbagai tempat di dunia (bahkan di tengah
keluarga kerajaan, di Ancient Rome dan Greece)—sampai di abad ke-20 dimana child marriage ini baru disadari sebagai sebuah masalah serius. Masalah
child marriage ini juga ternyata
sangat erat terkait dengan pemahaman agama masyarakat setempat, karena di
beberapa agama, child marriage dianggap
sesuai dengan nilai-norma agama yang
mereka anut.
Sayangnya,
child marriage adalah sebuah masalah
yang serius bagi para anak perempuan, baik dari sisi fisik, psikologis, pendidikan,
sosial, dan ekonomi. Bahkan, politik. Fisik tentu saja, karena di usia semuda
itu, organ kewanitaan anak perempuan belum benar-benar siap untuk reproduksi.
Angka kematian untuk anak-anak perempuan yang hamil di bawah umur sangat
tinggi. Hal ini masih ditambah dengan masalah sexual abuse yang mungkin terjadi, bahkan marital rape. Secara psikologis, mereka juga sebenarnya belum siap
menjadi istri apalagi ibu. Secara sosial, tentu saja mereka akan menghadapi
banyak tuntutan—belum lagi jika akhirnya suami mereka menceraikan atau
meninggalkan mereka. Dari sisi pendidikan, bagi para anak perempuan yang
kemudian dalam usia belia menjadi ibu, biasanya dengan sendirinya, akses
pendidikan ke mereka tertutup. Mereka harus jaga anak kan, dalam status baru
mereka sebagai ibu? Dan jika mereka sudah tidak bisa mengakses pendidikan yang
layak dan sewajarnya, akses kepada kesejahteraan ekonomi pun ikut
terminimalisasi. Belum lagi tanpa pendidikan, pengetahuan mereka soal dunia
luar akan menjadi terbatas dan sempit. Mereka mungkin tidak akan tahu apa itu
HAM, hak secara hukum, dan sederet pengetahuan gender lainnya. Termasuk politik.
Menjadi istri dan ibu di usia muda tanpa sebelumnya mengecap pendidikan yang
layak, akan mengungkung mereka pada pekerjaan ranah domestik yang pastinya menjauhkan
mereka dari ranah publik, dimana politik berkontestasi. Kecuali bagi beberapa
perempuan tertentu yang mungkin mendapat anugerah istimewa untuk menjadi para movement maker bagi kondisi yang
terjadi.
Bagi
kalian, para perempuan, yang membaca postingan ini (yang tinggal di perkotaan,
sedang atau sudah mengecap pendidikan tinggi, hidup dalam budaya yang
kontemporer dan lebih posmodern), mungkin berpikir masalah child marriage benar-benar jauh dari kehidupan kalian—sama seperti
saya juga, tadinya. Sampai saya sadar
bahwa di belahan dunia lain, bahkan di beberapa provinsi di Indonesia—wilayah-wilayah
developing countries—banyak anak
perempuan sudah, sedang, atau akan mengalami tragedi pernikahan anak ini. Apakah
kita tega untuk mendiamkannya saja? *
p.s. :
Lebih
banyak mengenai child marriage, kita
bisa mengakses data dari UNICEF, yang juga bisa didownload versi pdf. Selain
itu, dalam aksi browsing saya hari ini mengenai child marriage, saya juga menemukan website yang memperjuangkan
gerakan “Girls Are Not Brides”. Semoga mata dan hati kita semakin
terbuka untuk melihat betapa memprihatinkannya masalah child marriage ini. Salam sejahtera bagi semua (anak) perempuan di
seluruh dunia!



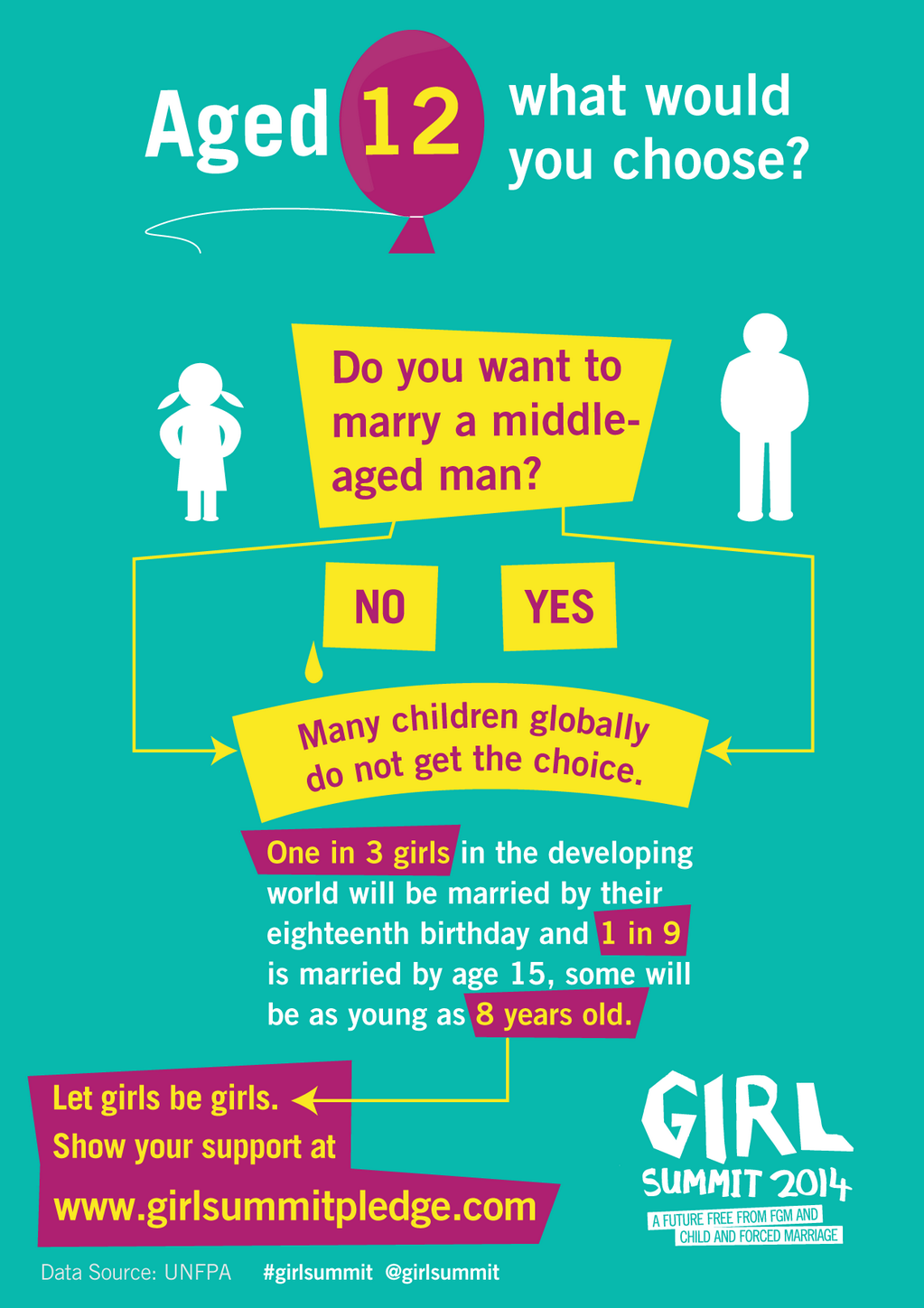




























No comments: